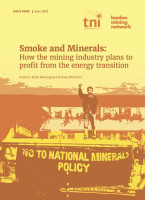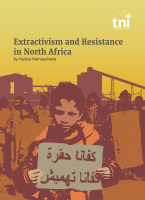Antara mineral dan posisi yang sulit Larangan ekspor mineral mentah Indonesia
Di era transisi energi, banyak pertanyaan tentang kontrol dan kekuasaan negara kembali menjadi agenda besar. Sekarang, semua dinamika ini muncul ke permukaan, terutama karena Amerika Serikat dan Uni Eropa - yang berusaha mengurangi ketergantungan industri mereka pada aktor-aktor Cina - mengejar berbagai kebijakan negara untuk mendapatkan akses dan kontrol yang lebih besar atas apa yang disebut sebagai transisi mineral. Artikel ‘Longread’ ini membahas beberapa ketegangan yang dihadapi negara Indonesia beserta dengan seluruh kebijakannya yang kontradiktif dalam menghadapi segalanya.

Illustration by Anđela Janković
Pendahuluan
Di era transisi energi, seluruh pertanyaan mengenai kontrol dan kekuasaan negara kembali menjadi agenda utama. Di tengah meningkatnya ketegangan geo-politik dan geo-ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, semua negara yang memiliki sumber daya kunci untuk teknologi de-karbonisasi (misalnya tembaga di pembangkit listrik tenaga angin, nikel dan litium di baterai kendaraan listrik) bergulat dengan apakah dan bagaimana mereka dapat meningkatkan posisi mereka. Tahun lalu, Meksiko menasionalisasi industri litiumnya, Zimbabwe melarang ekspor litium yang belum diproses dan baru-baru ini Presiden Chili yang berhaluan kiri, Gabriel Boric, mengumumkan peningkatan peran negara dalam industri litium nasional di sana. Negara Indonesia juga sedang menguji coba dengan membatasi ekspor mineral mentah.
Seluruh negara pemilik sumber daya alam ini sedang mencoba untuk menyeimbangkan tindakan mereka. Pada tingkat yang paling umum, semua negara di bawah kapitalisme menghadapi tantangan untuk di satu sisi memastikan perluasan akumulasi kapital yang berkelanjutan di dalam wilayah mereka, sementara di sisi lain mempertahankan tingkat legitimasi sosial yang minimum terhadap penduduknya. Khususnya dalam hal pertambangan, kedua tujuan ini sering kali bertentangan: perluasan industri pertambangan biasanya disertai dengan biaya sosial dan ekologis yang signifikan. Seolah-olah hal tersebut belum cukup, negara-negara ini - terutama yang lebih miskin - juga bergulat dengan segala pertanyaan mengenai industrialisasi nasional dan bagaimana menyeimbangkan hubungan antara modal asing dan modal nasional. Negara yang berani menempatkan persyaratan pada modal asing dan modal nasional dalam industri seperti pertambangan menghadapi ancaman langsung dari pelarian modal - seperti yang dilaporkan Financial Times dalam kalimat pertama liputannya tentang Chili, keputusan pemerintah “menciptakan ketidakpastian bagi para investor”. Sehubungan dengan Meksiko, surat kabar yang sama menulis pada tanggal 5 Juni 2023: “Perubahan undang-undang pertambangan, yang mencakup mempersulit perusahaan untuk mendapatkan konsesi mineral, mengancam akan memicu gelombang litigasi oleh para penambang Kanada yang berinvestasi di negara tersebut”. Selain itu, konflik dan kolaborasi antar negara juga berdampak pada manajemen masing-masing negara dalam menyeimbangkan undang-undang ini.
Semua dinamika ini muncul ke permukaan sekarang, terutama
karena Amerika Serikat dan Uni Eropa - yang berusaha mengurangi ketergantungan industri mereka pada aktor-aktor Cina - mengejar berbagai kebijakan negara untuk mendapatkan akses dan kontrol yang lebih besar atas apa yang disebut transisi mineral. Bacaan berikut ini membahas beberapa ketegangan yang dihadapi pemerintah Indonesia beserta seluruh kebijakannya yang kontradiktif dalam menghadapi segala tantangan ini. Pertama-tama, artikel ini membahas potensi ruang manuver untuk rencana industrialisasi nasional yang dibuka oleh transisi energi dan persaingan geo-politik. Kemudian beralih ke bagaimana ruang manuver tersebut ditantang oleh rezim perdagangan dan investasi internasional yang ada dan lebih jauh lagi, bagaimana rezim perdagangan dan investasi saat ini diperdalam dengan memeriksa kasus hubungan ekonomi Uni Eropa-Indonesia. Bacaan ini ditutup dengan beberapa pertanyaan yang menantang bagi kekuatan- kekuatan gerakan sosial di Indonesia dan di luar Indonesia.
Mineral “Kritis” pada saat yang kritis
Kebijakan larangan ekspor mineral mentah di Indonesia baru-baru ini menjadi sorotan dunia. Kebijakan ini dikeluarkan di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina, khususnya dalam persaingan mengamankan rantai pasokan mineral penting untuk memenuhi kebutuhan tren industri global di masa depan, yaitu industri energi berbasis teknologi digital dan ramah lingkungan. Ketegangan perdagangan Amerika Serikat- Cina, pandemi Covid-19, dan perang di Ukraina saat ini telah mengganggu rantai pasokan global, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang akses dan kontrol terhadap transisi mineral.
Gangguan ini disebabkan oleh ketergantungan yang signifikan dari perdagangan global terhadap pasokan produksi mineral yang terkonsentrasi hanya di satu atau dua negara, terutama Cina. Misalnya, Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Cina bertanggung jawab atas sekitar 70% dan 60% produksi global kobalt dan elemen bumi langka (rare earth) masing- masing pada tahun 2019, dan dalam operasi pemrosesan, pangsa pemurnian perusahaan-perusahaan Cina adalah sekitar 35% untuk nikel, 50-70% untuk litium dan kobalt, dan hampir 90% untuk elemen bumi langka (rare earth)1 (Lihat perusahaan-perusahaan Tiongkok teratas dalam rantai pasokan kendaraan listrik pada Tabel 1) Strategi Indonesia adalah untuk mengambil peran penting dalam kegiatan rantai pasokan dalam produksi baterai listrik global, khususnya untuk kendaraan listrik (EV). Pemerintah Indonesia menetapkan hal ini sebagai prioritas bagi industrinya pada tahun 2019. Pada tanggal 21 Desember 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan kembali larangan ekspor bauksit, yang akan mulai berlaku pada bulan Juni 2023, dan mewajibkan mineral tersebut untuk diproses dan dimurnikan di dalam negeri. Hal ini merupakan langkah kebijakan terbaru dari serangkaian keputusan yang dapat ditelusuri kembali ke tahun 20142 , ketika Indonesia melarang ekspor mineral mentah3 dan bijih Nikel pada bulan Januari 20204.
Di masa depan, kita dapat melihat beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia lainnya yang serua terkait pembatasan ekspor komoditas mineral mentah seperti tembaga dan timah. Selama tiga tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pusaran persaingan untuk mendapatkan akses ke mineral yang dibutuhkan dunia saat ini, terutama bagi negara-negara industri maju yang sedang mencari strategi untuk menjamin pasokan mineral penting dari luar Cina. Laporan International Energy Agency (IEA) tentang Peran Mineral Penting (critical minerals) dalam Transisi Energi Bersih (2021) menyatakan bahwa produksi dan pengolahan mineral terkonsentrasi hanya pada tiga negara produsen besar, dan hal ini berpotensi menimbulkan kerentanan pasokan akibat ketidakstabilan politik, risiko geopolitik, dan kemungkinan pembatasan ekspor.
Sebagai contoh, elemen tanah jarang secara berurutan hanya dikuasai oleh Cina, Amerika Serikat, dan Myanmar; sementara lithium secara berurutan dikuasai oleh Australia, Chili, dan Tiongkok; dan Nikel secara berurutan dikuasai oleh Indonesia, Filipina, dan Rusia5. (Lihat grafik 1)
Graph 1
|
N |
Tahap produksi |
Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 |
Pertambangan |
Ganfeng Lithium Co (Litium); Jinchuan Group (Nikel); Tsingshan (Nikel); Jinchuan group (Kobalt); CN Molibdenum (Kobalt) |
| 2 |
Pemrosesan Mineral Mentah |
Ganfeng (Litium); Chengxin Lithium Group; Zhejiang Huayou (nikel, Kobalt); Tsingshan (Nikel); |
| 3 |
Produksi Komponen Sel |
Tianjin B&M Science and Technology (katoda); Shenzhen Dynanonic (katoda); dan Ningbo Shanshan (katoda, anoda, & elektrolit); BTR New Energy Materials (anoda); Shanghai putailai new energy technology (anoda & separator); Zhuhai Enjie New Material Technologie (pemisah); Jiangxi Tinci Central Advanced Materials (elektrolit); Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials (elektrolit); Shenzhen Capchem Technology (elektrolit); |
| 4 |
Pengemasan Baterai |
CATL; BYD.co |
| 5 |
Produsen EV |
BYD.co; SAIC Motor (Wuling); |
Dengan cadangan nikel yang besar dan beberapa mineral penting untuk produksi baterai mobil listrik, negara Indonesia semakin percaya diri dalam upayanya untuk bergerak maju dengan agenda industrialisasi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Dalam pidato pelantikan untuk masa jabatan keduanya pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan dalam masa kepemimpinannya hingga tahun 2024. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ekspor untuk meningkatkan nilai tambah produksi telah diberlakukan sejak saat itu. Perubahan kebijakan ekonomi nasional ini bertujuan untuk mengubah Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pengekspor produk yang berdaya saing tinggi melalui industri hilir, terutama yang berbasis sumber daya alam. Agenda transformasi ekonomi tersebut diuraikan dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-20247.
RPJMN tersebut merupakan strategi pemerintah dalam menghadapi situasi pasca krisis 2008 yang terus memburuk dan diperparah dengan merebaknya Pandemi Covid-19. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia semakin memburuk akibat ketergantungan Indonesia pada perdagangan berbasis komoditas sumber daya alam mentah. Penurunan harga dan permintaan komoditas mentah dunia telah gagal mendongkrak penerimaan negara dan mengakibatkan ketergantungan impor, terutama bahan mentah/penolong industri, di pasar domestik. Oleh karena itu, pemerintah mengklaim bahwa industri hilir berbasis sumber daya alam akan dapat menghentikan ketergantungan dan meningkatkan konsumsi domestik serta membatasi impor sebagai cara untuk bertahan dalam situasi krisis. Semua ini juga diklaim akan memperkuat perekonomian nasional.
Landasan hukum terkait nasionalisasi
Banyak yang mungkin membayangkan bahwa keputusan Pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi nikel dan beberapa komoditas mineral lainnya hanyalah sebuah tanggapan terhadap tren peningkatan permintaan mineral global yang lebih baru, yaitu transisi menuju transisi ramah lingkungan. Namun, Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan tersebut satu dekade yang lalu, seolah-olah untuk memenuhi mandat Konstitusi bahwa "kekayaan alam dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat". Namun, untuk memenuhi mandat ini, diperlukan pengesahan dan implementasi undang-undang dan instrumen hukum untuk melaksanakannya, dan Indonesia telah mengesahkan serangkaian undang-undang dan instrumen hukum untuk mencapai tujuan tersebut.
Wicaksana (2019) berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia telah menggunakan Pasal 33 UUD 19459, yang sebagian menetapkan bahwa sektor-sektor produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, sebagai pembenaran untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Hal ini berlaku sejak era kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono yang mengusung model nasionalisme ekonomi, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, analisis Warburton (201810) menekankan bahwa terdapat kecenderungan umum terhadap intervensi negara yang lebih besar di sektor-sektor sumber daya, dan peningkatan pembatasan investasi asing sebagai upaya untuk memperkuat posisi ekonomi warga negara dan bangsa. Dalam konteks Indonesia, Warburton berargumen bahwa Indonesia mendapatkan reputasi sebagai negara yang ditandai dengan 'nasionalisme sumber daya' selama booming komoditas global, yang berlangsung sekitar tahun 2003-2013. Ia kemudian mengelompokkan kebijakan nasionalis ke dalam dua kategori: nasionalisme sumber daya yang melokalisasi,11 dan nasionalisme sumber daya yang mengindustrialisasi12.
Setelah gelombang pertama nasionalisme sumber daya alam pada era Soekarno, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pertambangan No. 4/2009, yang dikeluarkan pada masa kepresidenan Yudhoyono. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk memproses dan memurnikan produk pertambangan di dalam negeri sebelum diekspor, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral.13 Selain itu, bagian lain dari undang-undang ini juga bertujuan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan asing. Undang-undang ini secara efektif mewajibkan industri pertambangan yang dimiliki asing untuk melakukan divestasi secara bertahap untuk menjadi pemegang saham minoritas dalam waktu lima tahun.14 Saham-saham tersebut harus dialihkan kepada Pemerintah Indonesia melalui BUMN atau industri lokal - sehingga dalam waktu sepuluh tahun, 51% saham dimiliki oleh warga negara Indonesia15. Kewajiban dan persyaratan serupa telah ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Pertambangan No.3/2020 yang baru, yang mengamandemen Undang-Undang Pertambangan No.4/2009. Selain itu, pemerintah juga memasukkan kewajiban untuk menegosiasikan ulang kontrak karya bagi perusahaan pertambangan asing untuk mematuhi hukum lokal yang berlaku16.
Perlawanan Kritis Perusahaan
Undang-undang ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan-perusahaan kapitalis 'lokal', dengan berusaha membatasi modal asing yang aktif di wilayah Indonesia. Namun, upaya-upaya seperti itu jarang sekali tidak mendapat tantangan. Sejak tahun 2013, telah ada beberapa gugatan hukum, terutama oleh perusahaan-perusahaan pertambangan asing, untuk merevisi dan membatalkan kebijakan-kebijakan tersebut. Sebagian besar upaya tersebut telah gagal sejauh ini dan Pemerintah Indonesia terus menjamin pelaksanaan kewajiban pengolahan mineral mentah di dalam negeri di Indonesia sebelum diekspor sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, mencermati gugatan-gugatan hukum tersebut memberikan beberapa wawasan yang berguna tentang jenis perlawanan yang dihadapi Indonesia.
Pada tahun 2014, sembilan perusahaan pertambangan di Indonesia mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi17, terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU Minerba 4/2009, khususnya yang terkait dengan penerimaan hasil tambang di dalam negeri. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut, dan menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan konstitusi. Bagi Mahkamah, argumen yang diajukan oleh para pemohon (yaitu perusahaan-perusahaan pertambangan) tidak memiliki dasar, karena undang-undang tersebut memberikan waktu yang cukup bagi para pemohon dalam masa transisi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan pertambangan harus melaksanakan kewajiban pemurnian selambat-lambatnya lima tahun setelah diundangkannya UU tersebut. Mahkamah Konstitusi juga menyimpulkan bahwa sumber daya mineral dan batubara, dan sumber daya alam lainnya, dikuasai oleh negara, dan negara memiliki hak untuk mengatur sumber daya mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Contoh lain dari investor pertambangan asing yang menggugat kebijakan Indonesia ini adalah gugatan yang diajukan oleh Newmont (Nusa Tenggara Partnership BV), sebuah perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang terdaftar di Belanda, kepada International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada tahun 2014 dengan menggunakan Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia-Belanda (Indonesian-Belanda Bilateral Investment Treaty/IBIT)18. Gugatan tersebut didasarkan pada argumen Newmont bahwa larangan ekspor mineral mentah tidak sesuai dengan Kontrak Karya yang telah ditandatangani19. Pada akhirnya, Newmont mencabut gugatan tersebut setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang setuju untuk memulai proses negosiasi ulang Kontrak Karya. Dalam contoh lain, yang berpusat pada persyaratan divestasi saham asing dan kewajiban pengolahan mineral mentah, adalah ancaman Freeport McMoRan, sebuah perusahaan pertambangan AS, untuk menggugat Indonesia dan membawa kasus ini ke ICSID20. Kedua gugatan yang diajukan oleh perusahaan AS ini difasilitasi melalui mekanisme sengketa investasi internasional yang disebut Investor to State Dispute Settlement (ISDS).
|
ISDS adalah mekanisme yang termasuk dalam perjanjian investasi (bilateral) atau dalam bab investasi dalam perjanjian perdagangan bebas yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menuntut pemerintah di pengadilan ad-hoc internasional jika mereka dapat mengklaim bahwa hukum domestik mengurangi nilai investasi mereka. Ini adalah sistem yang berat sebelah dan tidak demokratis di mana negara selalu menjadi tergugat dan tidak dapat mengajukan tuntutan balik terhadap investor ke pengadilan yang sama. ISDS melangkahi yurisdiksi nasional. ISDS memberikan hak istimewa dan hak-hak khusus kepada investor asing, memberikan mereka kekuatan yang lebih besar dibandingkan warga negara dan pemerintah. Di seluruh dunia, mekanisme ISDS telah memperkuat kekebalan hukum korporasi, sekaligus melemahkan kekuasaan negara untuk mengatur praktik-praktik korporasi. Mekanisme ini sering kali menjadikan negara sebagai sandera bagi kepentingan investor, dan memungkinkan korporasi untuk menuntut ganti rugi miliaran dolar ketika mereka dapat mengklaim bahwa kebijakan nasional dalam beberapa hal telah merugikan investasi mereka21 . Pada akhirnya, negara membayar kompensasi dengan menggunakan uang publik, sehingga menimbulkan pertanyaan penting tentang keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kerugian publik. Selain itu, mekanisme ini memiliki efek dingin peraturan yang dapat mencegah negara membuat peraturan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Tentu saja, karena ekspor lebih banyak mineral mentah dilarang oleh pemerintah Indonesia, negara ini kemungkinan besar akan menghadapi berbagai ancaman tuntutan hukum ISDS dari investor asing - dan, perlu dicatat, mekanisme ISDS juga terbuka bagi perusahaan lokal selama mereka telah mendaftarkan perusahaan kotak surat di luar negeri di mana Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) menjamin akses ke mekanisme tersebut. Pada tahun 2015, Indonesia membatalkan banyak Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) setelah digugat oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tertentu dan mulai mengembangkan proposal perlindungan investasi alternatif berdasarkan habisnya upaya hukum lokal dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Negara ini kemungkinan besar akan menghadapi berbagai ancaman tuntutan hukum ISDS dari investor asing - dan, perlu dicatat, mekanisme ISDS juga terbuka bagi perusahaan lokal selama mereka telah mendaftarkan perusahaan kotak surat di luar negeri di mana Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) menjamin akses ke mekanisme tersebut. Pada tahun 2015, Indonesia membatalkan banyak Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) setelah digugat oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tertentu dan mulai mengembangkan proposal perlindungan investasi alternatif berdasarkan habisnya upaya hukum lokal dan bentuk- bentuk alternatif penyelesaian sengketa. |
|---|
Konflik Antar Negara
Di luar konflik antara negara dan kapital atas agenda nasionalisasi ini, ada juga konflik antara negara dan negara, seperti gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pembatasan ekspor nikel. Meskipun Ha-Joon Chang (200322) berpendapat bahwa masih ada ruang untuk bermanuver bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memaksakan kebijakan-kebijakan industri yang dapat digunakan secara sah di bawah rezim Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), ia juga berpendapat bahwa perselisihan yang sedang berlangsung di WTO mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan yang bebas dan adil, termasuk persaingan tidak sehat di antara para anggotanya, tidak akan hilang dengan mudah karena struktur pengambilan keputusan ‘demokratis’ yang formal di WTO.
Kasus yang dimaksud diajukan oleh Uni Eropa pada tanggal 22 November 2019, dengan mengajukan permohonan konsultasi terhadap Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Uni Eropa mengklaim bahwa pengenaan tindakan Indonesia untuk mencegah ekspor bijih nikel - yang dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas - tidak sesuai dengan Perjanjian Umum WTO tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT).
Keputusan Panel WTO mendukung Uni Eropa atas Indonesia, dengan Panel menyimpulkan bahwa langkah-langkah Indonesia untuk membatasi ekspor dan persyaratan pengolahan bijih nikel di dalam negeri telah bertentangan dengan Pasal XI: 1 GATT 1994 (Lihat Kotak-1). Namun, upaya Indonesia untuk mempertahankan kebijakan tersebut tidak berhenti, dan pada tanggal 8 Desember 2022, Pemerintah Indonesia mengajukan Banding ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Strategi kewajiban pengolahan dalam negeri (yang didorong dari pihak Indonesia) merupakan kebijakan penting bagi negara berkembang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaulat. Kebijakan ini memiliki potensi untuk mendukung upaya industrialisasi nasional dan berpotensi mengganggu pola perdagangan historis yang sangat bergantung pada ekspor komoditas primer, yang biasanya hanya menghasilkan sedikit pembangunan ekonomi. Kesimpulan Panel WTO menegaskan bahwa kedaulatan negara terus ditantang seperti yang ditunjukkan di sini, di mana aturan perjanjian perdagangan internasional mengalahkan Konstitusi Indonesia yang memberikan kontrol kepada negara atas sumber daya alamnya sendiri.
|
Dalam pembelaannya, Indonesia menggunakan Pasal XI:2 (a) GATT sebagai argumen untuk memperkuat penerapan kedua kebijakan tersebut: larangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri untuk produk nikel. Pasal tersebut mengijinkan anggota WTO untuk melarang atau membatasi ekspor untuk mencegah atau meringankan kekurangan bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pihak pengekspor. Indonesia mengajukan tiga alasan mengapa bijih Nikel penting bagi industri nasionalnya sehingga pemerintah harus memberlakukan pembatasan ekspor terhadap produk Nikel. Pertama, pentingnya pertambangan bagi perekonomian Indonesia, yang menyumbang sebagian besar PDB. Dalam hal ini, pemerintah mencatat bahwa Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia yang menyumbang 7% dari produksi global, dan pertambangan nikel berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan pemerintah dan lapangan kerja, serta memiliki arti penting secara ekonomi dan strategis di daerah-daerah miskin di mana nikel diproduksi, seperti di Sulawesi dan Maluku. Kedua, Indonesia berargumen bahwa nikel merupakan input yang sangat diperlukan untuk industri baja yang menyumbang 3,94% dari total PDB industri. Indonesia mencatat bahwa industri baja dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan dan hampir setengah dari permintaan baja Indonesia dipasok dari luar negeri. Ketiga, Indonesia menunjuk pada implementasi rencana strategis untuk memperluas produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia dalam jangka pendek, yang menghasilkan kebutuhan untuk mengamankan input penting untuk produksi tersebut, yaitu nikel. Ketiga alasan tersebut merujuk pada yurisprudensi kasus China-Raw Materials yang berkaitan dengan pembatasan ekspor bauksit China untuk memenuhi kebutuhan industri bajanya. Namun, dalam pertimbangannya, Panel WTO menjelaskan bahwa untuk dapat mengkategorikan kebijakan Indonesia memenuhi kriteria dalam pasal XI:2(a) GATT, Indonesia harus dapat membuktikan bahwa semua unsurnya telah terpenuhi. Dalam konteks bijih nikel sebagai produk esensial, Panel tidak mengecualikan kemungkinan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal XI: 2 (a) GATT 1994 dapat berhubungan dengan sumber daya alam yang terkuras. Namun, Indonesia harus menunjukkan bahwa tindakannya terkait dengan elemen kekurangan yang kritis (penekanan ditambahkan). Sehubungan dengan elemen ini, Panel WTO menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya kesamaan situasi antara kasus pembatasan Bauksit di Tiongkok dan kasus pembatasan Nikel di Indonesia. Menurut Panel WTO, langkah-langkah kebijakan Indonesia tidak dirancang untuk mengatasi kekurangan bijih nikel yang kritis untuk industri pertambangan. Produksi baterai kendaraan listrik belum dimulai di Indonesia dan hanya diproyeksikan untuk menjadi sumber lapangan kerja dan pendapatan bagi Pemerintah Indonesia di masa depan. Bagi Panel WTO, Indonesia telah gagal untuk membuktikan bahwa pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia telah memenuhi elemen-elemen dari Pasal XI:2 (a) GATT. Oleh karena itu, Panel menyimpulkan bahwa larangan ekspor dan kewajiban pengolahan di dalam negeri untuk produk bijih nikel Indonesia tidak dapat dikecualikan dari kewajiban dalam Pasal XI:1 GATT 1994 |
|---|
Memantik kemarahan perusahaan-perusahaan besar, berselisih dengan Uni Eropa
Seperti yang ditunjukkan di atas, upaya Indonesia untuk menyimpan bahan mentah di dalam negeri dan hanya mengekspornya setelah diolah bukannya tanpa perlawanan. Ke depannya, masih ada beberapa poin pertentangan lain yang akan muncul, khususnya bentrokan dengan mitra dagang internasional yang kuat yang mengandalkan akses tak terbatas terhadap bahan mentah Indonesia. Salah satu contoh yang menunjukkan hal ini adalah keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa (UE).
Baru-baru ini, Uni Eropa mengumumkan Undang-Undang Bahan Baku Kritis (Critical Raw Materials Act/CRMA) untuk memastikan bahwa Uni Eropa memiliki akses terhadap pasokan bahan baku kritis yang aman dan berkelanjutan yang sangat penting untuk transisi energi hijau23. Kerja sama perdagangan internasional merupakan bagian penting dari strategi ini untuk mendukung agenda menyeluruh dalam mendiversifikasi pasokan bahan baku penting Uni Eropa, dan di sinilah keputusan yang diambil oleh Uni Eropa akan sangat berdampak pada Indonesia. Uni Eropa bertujuan untuk mencapai tujuannya dengan memperluas perjanjian perdagangan bebasnya, memperkuat peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terutama untuk memastikan penegakan hukum terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak adil, memperluas jaringan Perjanjian Fasilitasi Investasi Berkelanjutan (Sustainable Investment Facilitation Agreements), termasuk mencari kemitraan yang saling menguntungkan dengan pasar negara berkembang dan negara berkembang di bawah kerangka kerja Strategi Gerbang Global (Global Gateway Strategy)24.
Uni Eropa bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dengan beberapa negara strategis, seperti Indonesia, Chili, Meksiko, Selandia Baru, Australia, dan India. Dalam konteks ini, di mana Uni Eropa berusaha untuk mendapatkan sumber bahan baku alternatif dan terjamin, gugatan Uni Eropa di WTO terhadap kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia menjadi lebih masuk akal. Ini adalah salah satu strategi Uni Eropa untuk melawan pembatasan ekspor yang telah meniadakan dan merusak manfaat yang diperoleh Uni Eropa di bawah perjanjian WTO.
Berbagai aspek dari berbagai perjanjian perdagangan Uni Eropa menimbulkan masalah bagi kebijakan Indonesia: banyak perjanjian yang memiliki bab khusus mengenai Energi dan Bahan Mentah, yang mencakup klausul-klausul seperti prosedur penilaian dampak yang dapat diprediksi atau perlakuan non-diskriminasi bagi investor di negara ketiga. Selain itu, beberapa bab Energi dan Bahan Mentah (Energy and Raw Materials - ERM) dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa yang baru saja disepakati berisi ketentuan keberlanjutan yang spesifik, yang dirancang untuk memenuhi komitmen Uni Eropa terhadap standar-standar keberlanjutan dan hak asasi manusia yang tinggi. Beberapa perjanjian perdagangan Uni Eropa memiliki bab terpisah tentang perdagangan dan pembangunan berkelanjutan yang mengikat mitra dagang dengan perjanjian internasional dan standar hak asasi manusia, pekerjaan yang layak, iklim dan lingkungan.
Kehadiran EU Critical Raw Materials Act akan memberikan tantangan tersendiri dalam pembahasan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, terutama terkait dengan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Penyelesaian negosiasi IEU CEPA yang masih berlangsung akan menjadi langkah penting bagi Uni Eropa untuk mengimplementasikan agendanya dalam mengamankan akses terhadap bahan baku kritis.
Selama tujuh tahun, negosiasi IEU CEPA telah menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait ketidaksesuaian antara kebijakan ekonomi Uni Eropa dan Indonesia. Indonesia memprotes peraturan lingkungan hidup Uni Eropa yang berpotensi menghambat akses pasar untuk beberapa komoditas, seperti kelapa sawit dan hasil hutan lainnya. Di sisi lain, Uni Eropa juga memiliki beberapa keberatan terhadap kebijakan Indonesia, terutama yang terkait dengan investasi dan pembatasan ekspor bahan baku Indonesia25.
Meskipun Uni Eropa berkomitmen untuk membangun kemitraan strategis pada rantai nilai bahan baku yang penting dengan mendukung penciptaan nilai di dalam negeri dari mitra negara ketiga, masih belum jelas bagaimana Uni Eropa akan melakukan hal ini dengan Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia juga memiliki ambisi untuk mengembangkan industri energi terbarukannya sendiri, khususnya industri baterai untuk kendaraan listrik.
Dalam upayanya untuk merealisasikan rencananya, Indonesia akan membatasi beberapa ketentuan liberalisasi, seperti larangan persyaratan konten lokal26, transfer teknologi, dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan tentang beberapa kebijakan proteksionis Indonesia di bidang energi dan bahan baku, yang berpotensi menghambat pasokan bahan baku yang sangat penting bagi kebutuhan Uni Eropa. Beberapa kekhawatiran dari Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia disebutkan di bawah ini dalam kertas kerja IEU CEPA:
"Sektor energi dan bahan baku Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang besar. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dengan produksi minyak dan gas serta mineral dan logam yang signifikan. Pada saat yang sama, Indonesia mempertahankan sejumlah langkah pembatasan perdagangan dan investasi yang memiliki dampak negatif pada pasar domestik dan internasional energi dan bahan baku. Langkah-langkah proteksionis tersebut termasuk larangan ekspor mineral yang belum diolah yang diperkenalkan pada tahun 2014, persyaratan konten lokal, larangan privatisasi BUMN di sektor sumber daya alam, serta subsidi energi."27
Faktanya, kedua pihak telah secara berkala berselisih dalam sengketa perdagangan di WTO. Dimulai dengan gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa yang membatasi akses pasar untuk produk minyak kelapa sawit Indonesia28, yang kemudian dibalas dengan gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel29. Meskipun Indonesia kalah dari UE dalam kasus pembatasan ekspor bijih nikel, Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Pada bulan Januari 2023, Indonesia kembali mengajukan gugatan terhadap UE terkait pembatasan produk baja nirkarat dari Indonesia30.
Terlepas dari banyaknya tantangan yang dihadapi oleh IEU CEPA, para pemimpin negara telah sepakat untuk menyelesaikan negosiasi pada akhir tahun 202331. Tiga isu krusial dalam perundingan IEU CEPA akan menentukan kemajuan penyelesaian perundingan, yaitu bab investasi, bab energi dan bahan baku, serta bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, yang mempengaruhi nuansa perundingan.
Kemungkinan besar, penyelesaian negosiasi akan sangat bergantung pada pertukaran dan kesepakatan bisnis swasta yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak, terutama karena Indonesia berharap untuk menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Eropa. Masih harus dilihat apakah pertukaran tersebut akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Kedaulatan, demokrasi, dan keadilan lingkungan? Beberapa pertanyaan untuk direnungkan
Meskipun Indonesia telah melakukan banyak hal untuk melindungi kepentingan nasionalnya sendiri dengan mengatur kegiatan modal internasional dan mengeluarkan kebijakan yang melindungi industri lokal, bukan berarti tidak ada kontradiksi. Indonesia masih harus melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa kelimpahan mineral transisinya tidak berubah menjadi "kutukan sumber daya" yang sering disebut-sebut. Masih ada pertanyaan-pertanyaan penting mengenai proses demokrasi, pertanyaan-pertanyaan mengenai kesetaraan dan keadilan dalam praktik-praktik ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup setempat, dan keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan penduduk setempat. Selain itu, negara-negara lain yang telah memulai jalur nasionalisasi sumber daya alam telah menghadapi banyak konsekuensi yang mengerikan dengan adanya pelarian modal, dan dalam beberapa kasus embargo atau sanksi.
Tidak dapat disangkal bahwa banyak negara perlu mengembangkan industri lokal mereka sendiri dan tidak kehilangan semua keuntungan dari sektor pertambangan melalui ekspor. Tidak dapat disangkal bahwa ada kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan industri lokal tersebut, baik melalui insentif maupun pembatasan. Namun, sisi lain dari pertanyaan tersebut adalah, siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan-kebijakan ini? Apakah keuntungan yang didapat oleh modal lokal cukup untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan untuk lingkungan dan kondisi tenaga kerja lokal? Bagaimana seharusnya organisasi dan akar rumput mengorientasikan diri mereka dalam lanskap yang berubah dengan cepat ini? Bagaimana mereka dapat merumuskan tuntutan yang efektif, koheren dan bersama untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh secara luas dapat dirasakan oleh masyarakat, dan bukan hanya oleh kelas elit kapitalis internal? Sudah ada tanda-tanda ketegangan ini.
Sebagai contoh, tujuan industrialisasi hilirisasi Indonesia yang berbasis sumber daya alam membutuhkan ekspansi geografis berskala besar untuk industri pertambangan dan pengolahan. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2021, terdapat total 339 izin aktif untuk bisnis pertambangan Nikel, baik eksplorasi maupun produksi, dengan total luas area yang tersebar seluas 836.000 hektar. Jika kita memperhitungkan pembangunan infrastruktur yang diperlukan melalui perluasan kawasan ekonomi khusus baru yang ditetapkan di beberapa wilayah Indonesia, serta pengembangan sumber energi untuk mendukung perluasan ini, maka semua itu terbaca seperti resep yang ditulis oleh bank dunia32. Kemungkinan terjadinya perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan pertanyaan kritis bagi para aktivis iklim, lingkungan dan hak asasi manusia. Apakah prospek pertumbuhan ekonomi benar-benar layak untuk mengorbankan hak-hak sosial dan lingkungan yang penting dalam jangka pendek? Apakah pertumbuhan ekonomi tersebut akan menguntungkan Indonesia dan mendorong Indonesia menuju transisi yang adil, atau hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang sama yang telah membawa kita ke jurang bencana iklim? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tidak mengherankan jika beberapa aspek kebijakan pemerintah Indonesia telah menimbulkan perlawanan internal dari beberapa sektor masyarakat Indonesia.
Sudah ada konflik penggunaan lahan antara pemerintah dan petani Indonesia. Sebagai contoh, industri peleburan nikel berbasis High-Pressure Acid Leaching (HPAL) di kawasan Kawasan Industri Pomala, Sulawesi Tenggara, yang dimiliki oleh PT. Vale Indonesia bekerja sama dengan Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited (Huayou) telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Pemerintah. Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat perlindungan dari berbagai bentuk regulasi untuk mempermudah pembebasan lahan, yang berujung pada praktik perampasan tanah. Pada tahun 2021, misalnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat hingga 40 konflik agraria yang disebabkan oleh PSN. Konflik tersebut terjadi di area seluas 11.466,923 ha atau 49,8% dari total luas lahan yang dibutuhkan untuk PSN. Konflik-konflik ini kemungkinan besar akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya proyek pertambangan dan smelter yang disetujui.
Selain itu, industrialisasi Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing, yang menyebabkan kontradiksi-kontradiksi lainnya. Pada saat yang sama ketika pemerintah membuat marah investor asing dengan persyaratan kepemilikan lokal, penambahan nilai dan pelarangan ekspor, pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk menarik investor yang sama, dengan menargetkan US$ 30,9 miliar sebagai total investasi untuk industri rantai pasokan baterai EV di Indonesia33. Dalam rangka merayu investasi asing untuk mendukung kebijakan industri ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nasional yang kontroversial yang disebut Omnibus Law tentang Penciptaan Lapangan Kerja yang memfasilitasi akses ke izin usaha untuk investor asing, termasuk izin untuk mengakses sumber daya alam dan menyewa tanah. Aspek-aspek dari undang-undang tersebut juga sangat melemahkan hak-hak buruh di Indonesia.
Beberapa ahli berpendapat di Mahkamah Konstitusi bahwa omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja sangat kontroversial. Undang-undang ini dianggap cacat secara prosedural, terutama dalam upayanya untuk menderegulasi lusinan undang-undang dan menggantinya dengan hanya satu omnibus law. Kritik dan keberatan tidak hanya datang dari kelompok buruh, tetapi juga dari aktivis lingkungan, organisasi petani dan nelayan, mahasiswa, akademisi dari puluhan universitas di Indonesia, dan beberapa organisasi keagamaan terkemuka yang menganggap undang-undang tersebut merugikan hak-hak buruh dan lingkungan. Mereka juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut disahkan melalui proses yang tidak demokratis dan tidak dapat dinilai oleh publik34.
Pada tanggal 25 November 2022, Mahkamah Konstitusi di Indonesia menyatakan bahwa Omnibus Law secara formal cacat dan tidak konstitusional secara bersyarat. Namun, Pemerintah dan DPR mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi dan mengesahkan Omnibus Law dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)35. Oleh karena itu, mandat konstitusional yang memberikan pembenaran atas kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia juga memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat sipil dan buruh, dan perlu digugat dalam konteks implementasinya. Secara khusus, jika hubungan antara negara dan korporasi sangat kuat dalam hal mengendalikan bisnis dari hulu ke hilir, hal ini dapat membatasi kemungkinan demokratisasi transisi energi untuk rakyat dan planet yang berkelanjutan. Masyarakat sipil Indonesia harus menemukan cara untuk menghadapi semua kontradiksi ini.
Seperti yang telah disebutkan di bagian pembuka tulisan ini, dinamika yang terjadi saat ini di Indonesia dan berbagai negara pemilik sumber daya alam lainnya memunculkan sejumlah pertanyaan penting yang perlu digumuli oleh gerakan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya. Dalam konteks meningkatnya persaingan geo-politik dan geo-ekonomi, apa saja peluang industrialisasi nasional bagi negara-negara pemilik sumber daya alam (seperti Indonesia) dan peran apa yang dapat dimainkan oleh negara dalam proses ini? Dapatkah modal (asing dan lokal) didisiplinkan melalui kepemilikan publik dan demokratis atas sumber daya alam untuk memainkan peran yang mendukung dan diarahkan oleh negara dalam upaya industrialisasi semacam itu? Apakah dan bagaimana ekstraksi untuk transisi energi dapat dilakukan dengan cara yang adil secara sosial dan lingkungan? Sejalan dengan itu, apakah ekstraksi tanpa apa yang disebut sebagai 'ekstraktivisme' itu mungkin dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengembangkan strategi yang sesuai akan membutuhkan analisis dan perdebatan yang serius dan ketat.